Perempuan tidak hanya dinomorduakan, perempuan juga tidak berhak tahu banyak hal, pun mencintai dirinya sendiri. Begitu lah Desa Ketan memperlakukan kami.
Aku sendiri tidak begitu paham apa
yang melatarbelakangi sebutan desa kami. Hanya anak laki-laki lah yang
mendapatkan penjelasan secara detail asal muasal namanya. Yang jelas kutahu,
masyarakat di sini selalu menghidangkan menu ketan pada setiap perayaan atau
acara keluarga. Menu-menu ketan tersebut diolah dengan varian yang berbeda-beda.
Ketan kacang di selametan sunatan, ketan cokelat pada ritual empat bulan
kehamilan. Begitu pula ketika perayaan pernikahan, kami membuat menu ketan dengan
topping buah-buahan seperti duren, mangga,
pisang, atau stroberi.
Di desa kami, panorama pada sore
hari menyuguhkan keindahan alam yang hampir sempurna indahnya. Selain
menghasilkan ketan yang melimpah, desa ini juga memiliki kekayaan udara yang
sejuk dan pancaran cahaya yang hangat. Itulah mengapa aku dan ketiga rekanku
memilih waktu sore untuk saling bertemu.
Selain karena urusan rumah dan
pelajaran wajib telah usai, sore hari di sini sangat cocok untuk dilalui dengan
belajar. Diam-diam kami keluar rumah untuk belajar hal baru di luar pelajaran
memasak, berdandan, dan pelajaran mengurus rumah atau bab tentang membina rumah
tangga. Itu adalah perihal wajib belajar kami sejak usia dini, sebuah
konsekuensi terlahir sebagai anak perempuan. Di luar pelajaran-pelajaran itu,
kami tidak diperbolehkan mempelajarinya. Bahkan kesempatan bisa membaca hanya didapatkan
anak laki-laki. Keluarga perempuan ketua adat pun dilarang karena sebuah
alasan.
“Ayah, mengapa anak perempuan tidak
diperbolehkan belajar di luar pelajaran wajib desa ini?” tanyaku pada Ayah
suatu hari.
“Perempuan tidak membutuhkan selain
perihal itu, Nak!” Aku kecewa dengan jawabannya dan ingin kubantah namun belum
ada cukup keberanian yang kupunya. Ayahku adalah ketua adat di desa kami
setelah wafatnya kakek yang sudah dua puluh tahun dihormati sebagai ketua adat
sebelumnya. Ayah adalah sosok yang punya watak keras dan tegas. Belum sekali pun
aku membantah perintahnya. Begitupun dengan warga Desa Ketan yang amat
menjunjungnya.
“Ayah, aku ingin sekolah!” ujarku
kemudian.
“Tidak boleh!”
“Ayah! Mengapa aku tidak boleh,
tapi abang-abangku boleh?”
Ayah tidak menggubrisku seperti
biasanya. Setiap awal tahun, aku selalu menanyakan dan meminta hal yang sama.
Dan ayah tetap saja konsisten dengan jawabannya hingga usiaku 12 tahun.
***
Pada kegiatanku yang belajar secara
diam-diam, hanya ada tiga perempuan di desa ini yang mau melakukannya bersamaku.
Perempuan-perempuan lain lebih memilih aman dan mencukupkan diri dengan apa
yang telah didapatkannya selama ini. Setiap dua hari sekali kami bertemu untuk
mengajari tiga rekanku membaca.
Semenjak berusia dua belas tahun,
aku mulai belajar membaca dan mencari tahu pengetahuan lain di luar pelajaran
wajib dari orang tua. Aku memaksa Nesi, salah satu abangku untuk mengajariku
membaca. Awalnya dia menolak, tapi lama-lama dia tidak tahan menghadapi
rengekanku yang berisik di telinganya setiap hari.
Tidak butuh waktu lama untuk
menyerap pelajaran dari Bang Nesi. Dalam kurun waktu enam bulan aku sudah bisa
membaca dengan lancar. Aku benar-benar bertekad untuk segera bisa mengetahui isi
buku-buku di lemari rumah yang sering membuatku penasaran.
Pertemuanku dengan Ros, Melani, dan
Zuma dilakukan di bawah pohon besar yang tidak jauh dari rumah namun jarang
dilewati masyarakat desa. Jadi bisa dibilang aman untuk belajar secara
sembunyi-sembunyi di sana. Kami menggali tanah di sekitar akar pohon itu untuk menyembunyikan
buku-buku yang kami pelajari dalam sebuah kotak rahasia.
Pohon yang kumaksud sebagai tempat
belajar kami adalah satu pohon yang amat besar di desa ini. Pohon yang belum
punya nama. Masyarakat pun bingung untuk memberinya nama karena selama pohon
itu tumbuh di tujuh ratus meter dari rumahku, ia belum pernah sekalipun
berbuah. Bukan hanya sebab itu, bentuknya juga berbeda dari pohon-pohon lainnya.
Kalau dihitung-hitung, pohon
tersebut sudah berumur enam puluh empat tahun. Seumuran dengan ayahku. Pohon
tak bernama ini mulai ditemukan sejak ayah berusia satu tahun. Waktu itu ayah
sedang jalan-jalan bersama kakek ke kebun dan melihat sesuatu yang janggal dari
sekian tanamannya itu. Ia menemukan satu tumbuhan langka. Bentuk batangnya
seperti pohon nangka, namun daunnya memiliki bentuk mirip daun talas. Kakek
juga melihat pohon tersebut berbunga dengan bentuk seperti melati, namun aroma
yang dihasilkannya tidak jauh berbeda dengan wanginya bunga kamboja. Sejak saat
itu, ia merawatnya dan membiarkan pohon tersebut terus tumbuh dengan
keanehannya tersebut di kebunnya.
***
Waktu terus berlalu dan aku tetap
rutin berkunjung ke pohon tak bernama itu. Begitu pun dengan Ros, Melani, dan
Zuma. Kini mereka juga bisa membaca dan satu persatu buku ayah atau saudara
laki-lakinya dibawa untuk bisa kami baca. Kami belajar tentang astronomi,
biografi tokoh-tokoh terkenal, ilmu ekonomi, sesekali tentang filsafat, dan
masih banyak lagi yang kami baca. Menyenangkan sekali mengetahui lebih banyak
hal.
“Enim, mengapa kita perlu belajar membaca?
Pelajaran wajib saja sudah terasa cukup untuk membekali masa depan kita.” Ros
masih belum yakin dengan ajakanku untuk belajar hal baru. Dia terus saja
bertanya di awal-awal pertemuan kami.
“Apakah suamimu sering mendapat
surat dari temannya?” Aku tidak langsung menjawab pertanyaannya. Lantas aku
menimpalinya pertanyaan lain. Si Ros yang sudah menikah sejak usia sepuluh
tahun ini terheran-heran.
“Iya, setiap bulan datang surat
baru dari sahabatnya di luar daerah untuk bertukar kabar.” Meskipun heran,
tetap saja dia menjawab pertanyaanku.
“Dari sekian surat yang ditujukan
untuk suamimu itu, bisa saja satu atau dua surat berisi tentang perempuan lain
yang diperkenalkan sahabatnya. Sebuah rencana perselingkuhan dengan perempuan
yang lebih cantik darimu. Kamu tidak akan tahu, karena kamu tidak bisa
membacanya,” ujarku dengan intonasi meyakinkan.
Ros tiba-tiba diam dan tidak bertanya lagi setelah mendengar ucapanku barusan.
Setelah percakapan ini, dia semakin giat belajar membaca dan mulai menemukan
sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya.
Tidak lama setelah Ros bisa
membaca, ia memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Diam-diam dia membaca
surat dari sahabat suaminya itu, dan pengandaian yang kukatakan padanya
benar-benar terjadi tanpa kuduga.
Setelah mengetahui perihal perceraian
tersebut, Melani dan Zuma tiba-tiba berbisik di tengah-tengah diskusi kami.
“Beri aku alasan mengapa membaca
itu penting. Beri alasan dengan pengandaian yang baik ya, Nim,” ucap Zuma pelan
di telingaku.
“Padaku juga, Nim. Aku tidak mau
seperti Ros. Ucapanmu ternyata sakti mandraguna,” bisik Melani kemudian di
telingaku yang lain.
***
Dua tahun kami belajar secara
diam-diam, dua tahun pula kami berpura-pura tidak mengetahui apapun selain yang
diajarkan desa ini untuk kaum perempuan. Sebelum matahari tenggelam, kami sudah
harus berada di rumah masing-masing agar tidak ketahuan.
Suatu hari, kami berempat asyik
sekali membaca buku di pohon tak bernama. Dari saking asyiknya, kami tidak
menyadari bahwa hari mulai gelap. Aku memaksakan diri terus membaca menggunakan
senter karena sedikit lagi buku itu akan kutamatkan. Tanpa kami sangka, empat
keluarga tersadar anak perempuan mereka tidak ada di rumah saat matahari
tenggelam. Mereka menemukan kami setelah mencari ke seluruh sudut desa.
Ayah tampak sekali geram saat
melihat aku tengah membaca. Ia berteriak keras sekali sembari menghampiriku.
Menyeretku dari pohon tak bernama menuju rumah tanpa rasa kasihan sedikit pun.
Aku sungguh terancam waktu itu. Rasanya aku akan mati saat itu juga. Ayah
mengikat kami berempat di tiang depan rumah semalaman. Tak peduli hujan deras,
angin badai, petir menyambar, kami tetap diikat hingga matahari membawa pagi
lagi.
Kemarahan Ayah selaku ketua adat
menggemparkan seantero desa. Tidak hanya aku dan tiga temanku yang belajar
diam-diam yang merasakan takut, namun seluruh penduduk Desa Ketan turut
merinding dengan kemarahan Ayah. Kini aku dilarang keluar rumah. Begitu pun
dengan Ros, Melani, dan Zuma. Pohon tak bernama itu akan ditebang agar aku
tidak memiliki tempat persembunyian lagi untuk melanggar perintahnya. Aku tidak
bisa membayangkan bagaimana bosannya hidupku nanti ketika pohon itu benar-benar
ditebang. Pasalnya, aku telah menemukan cara untuk mencintai diriku sendiri dan
tidak lama lagi hal tersebut akan kandas.
Oya, ada satu hal yang belum
kuceritakan. Empat bulan sebelum perbuatan belajar kami yang sembunyi-sembunyi
ini ketahuan, selalu ada seekor babi di bawah pohon tak bernama ketika kami tiba
di sana. Namun babi tersebut pergi setelah mengetahui kedatangan kami. Aku
sendiri tidak tahu dari mana asal babi itu. Ia terlihat jinak dan sepertinya
sudah tua. Biasanya sebelum pergi, ia berputar tiga kali mengelilingi pohon tak
bernama sembari mengendus dan menggoyang-goyangkan pantatnya. Tidak lama
setelah memutari pohon, kakinya mengeruk tanah dan membuat lubang kecil di
sekitarnya. Rutinitas tersebut terus berlangsung hingga babi asing itu berhasil
membuat sebuah lubang cukup dalam yang
dia keruk setiap kali kami datang. Aku dan teman-temanku membiarkan saja
selama babi tersebut tidak mengganggu belajar kami.
Satu minggu sebelum ditebangnya
pohon tak bernama, salah satu warga membawa informasi bahwa ada seekor babi
mati di bawah pohon langka tersebut. Seorang warga itu melapor karena tidak
biasanya ada babi di desa kami. Ia khawatir itu merupakan pertanda buruk. Ia
mengabarkan bahwa babi yang mati itu terperosok ke dalam sebuah lubang cukup
dalam. Aku meyakini, ia mati bukan
karena terperosok ke dalam lubang seperti yang dipikirkan orang kebanyakan.
Namun babi itu sengaja menguburkan dirinya di jurang yang ia gali sendiri.
Sebuah perkara hidup yang menakjubkan.
“Biarkan saja babi itu di sana.
Timbun bangkainya dengan tanah,” perintah ayahku pada warga yang melapor. Dia
kembali ke tempat pohon tak bernama berada untuk segera melaksanakan perintah.
“Babi berbuah! Babi berbuah! Babi
berbuah! Babi berbuah!” Teriakan yang memekakkan telinga terdengar dari Pembawa
kabar kematian babi setengah jam kemudian. Ia terus meneriakkan kalimat itu
sembari berlari tunggang langgang ke arah rumah.
“Babi berbuah! Babi berbuah! Babi berbuah!
Babi berbuah!” Kali ini aku tidak salah lagi. Dia memang berteriak Babi
berbuah. Hah, babi berbuah?
Warga lainnya berkerumun mendekatinya
dan dia masih saja meneriakkan kalimat yang sama.
“Ada apa? Ada apa?” Tanya warga
dalam kerumunan.
“Babi Berbuah!” Semua orang diam
hendak mendengar secara jelas kalimat seorang warga yang berteriak tadi. “Maksud
saya pohon tak bernama itu kini berbuah!” lanjutnya dengan girang. Semua orang
masih terdiam. Menunjukkan ketidakpercayaan dan masih penasaran dengan kalimat
‘Babi Berbuah’. “Mari kita ke sana sekarang!” ucapnya lagi mencoba meyakinkan
semua orang tentang omongannya yang terdengar konyol.
Tanpa berpikir lama lagi, Ayah
beserta penduduk desa yang berkerumun bergegas menuju pohon tak bernama.
Sepanjang perjalanan, suara desas-desus warga terus terdengar. Percaya tidak
percaya, kami semua langsung terperangah dan heran seketika melihat pemandangan
di depan kami. Suara desas-desus ataupun kasak-kusuk spontan hilang. Senyap
tiba-tiba.
“Sebuah keajaiban!” Lontar Ayahku
menerobos kesenyapan. Sontak semua warga bersorak riang dan berucap syukur. Kamu
mungkin lebih memilih tidak percaya ketika mendengar cerita ini. Aku yang
menyaksikannya secara langsung masih berpikir ini mimpi. Pohon tak bernama itu
sungguh berbuah. Yang lebih menggembirakan lagi, buahnya serupa dengan beras
ketan yang kami tanam sepanjang tahun. Pohon tak bernama yang berbatang seperti
nangka, berdaun mirip talas, lalu berbunga dengan bentuk melati beraroma
kamboja kini berbuah beras ketan begitu lebatnya melebihi panen akbar yang
selalu kami tunggu.
Tiga hari kemudian, warga Desa
Ketan mengadakan pesta besar. Sebuah perayaan sebagai tanda syukur kami kepada
yang Maha Kuasa atas rezeki yang dilimpahkan begitu banyaknya. Pohon tak
bernama itu kini semakin lengkap keajaibannya. Kami menghidangkan beraneka
macam varian masakan ketan lebih dari perayaan-perayaan biasanya.
Terlebih lagi, setelah aku
menceritakan perihal babi yang dipercaya sebagai salah satu perantara
berbuahnya pohon langka kami, ada ritual baru yang lahir karenanya. Pada
perayaan ini pula yang kemudian disebut dengan “Perayaan Babi Berbuah”, Ayah
membatalkan penebangan pohon tak bernama dan memperbolehkan kami melakukan
kegiatan belajar di sana. Khususnya para perempuan Desa Ketan.
Aku tak bisa berkata-kata apalagi
setelah pengumuman yang amat menggembirakan itu. Aku pun tidak penasaran
mengapa tiba-tiba Ayah berubah pikiran. Dalam hati aku tak hentinya bersyukur
dan mengenang dengan sangat baik tentang babi yang kini sudah mengubur dirinya
sendiri.
“Kamu tahu apa alasan perempuan di
sini dilarang belajar membaca dan mempelajari hal lain di luar urusan rumah
tangga?” Pertanyaan Abang Nesi mengagetkan aku yang tengah bereuforia.
“Ayah tidak pernah sekalipun
menjawab pertanyaanku tentang itu,” aku menjawabnya sembari menggelengkan
kepala berkali-kali.
“Karena kalau kalian bisa membaca
apalagi lebih pandai dari para lelaki, kalian akan lebih sering membantah dan
bisa-bisa lupa atau lalai pada tugas utama perempuan dalam tatanan desa ini.
Seperti kejadian dua puluh tahun silam.”
“Ada apa, Bang di dua puluh tahun
silam?”
“Kakek mengutuk saudara perempuan
Ayah menjadi babi karena ia melalaikan tugas utamanya sebagai anak perempuan.
Itu karena dia terlalu asyik membaca hingga lupa waktu dan tidak melaksanakan
tugas keperempuanannya dengan benar.”
“Lalu apa yang terjadi padanya?”
“Ia pergi dari desa ini dan tidak
ada yang tahu apakah kutukan itu benar-benar terjadi padanya atau tidak.” Aku
mulai mereka-reka apa yang terjadi kemudian dengan bibiku itu. Berbagai
kemungkinan muncul di benakku. Pertanyaan-pertanyaan susulan tiba-tiba
menyeruak di kepala namun tidak sanggup kuutarakan.
“Mungkinkah babi itu….” Suaraku
tercekat. Tidak sanggup kuteruskan.
“Aku tidak tahu. Aku tidak berani menyimpulkan, Nim.”
***
*cerpen ini juga diunggah di platform Storial
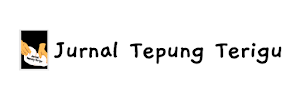







Post a Comment
Post a Comment